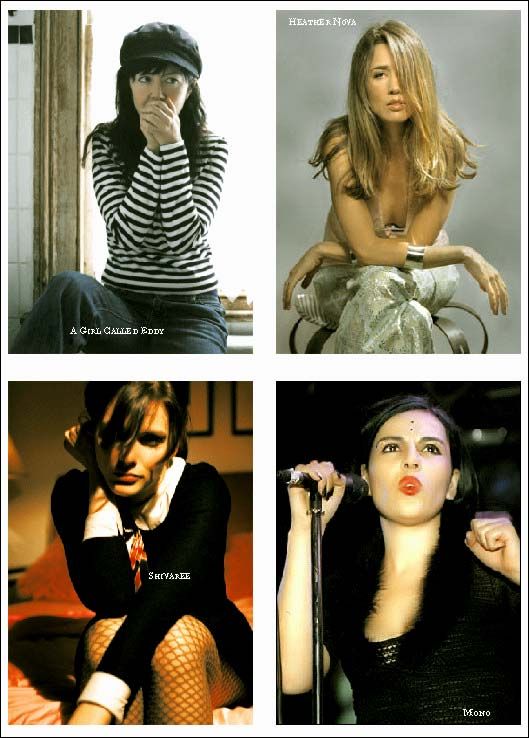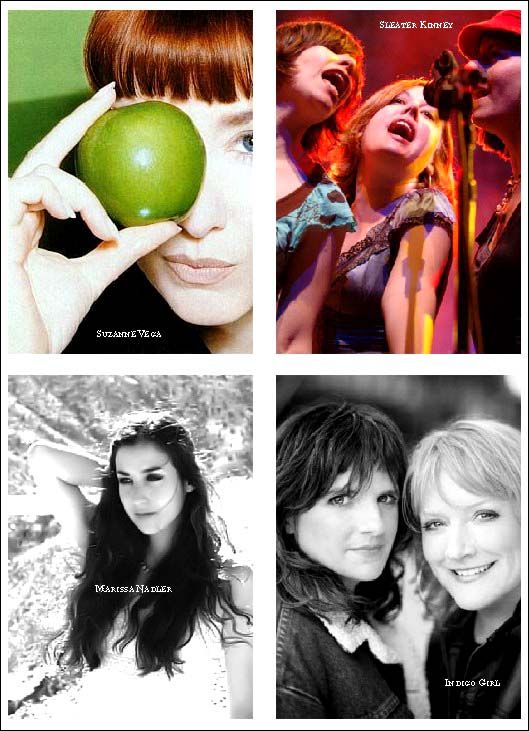Tahun 1969, event Woodstock menggariskan suatu bentuk keterlibatan musik dalam bidang politik, isu internasional dan kemanusiaan. Festival yang menjadi simbol kepekaan manusia itu melahirkan ikon-ikon pejuang musik dalam diri Bob Dylan, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, dan sebagainya. Di tahun 1994, sekuel event tersebut coba digagas ulang. Kali ini dengan isu sensitif peralihan generasi (genX), lebih kepada bentuk kesadaran. Hampir berhasil, tetapi tetap saja muatannya lebih komersil. Mungkin dari sederet, Bob Dylan kembali hadir mengaskan ikon festival ini bersama Peter Gabriel dan Cypress Hill. Lima tahun berselang, ajang ini sudah murni menjadi ajang komersil ketika deretan musisi semacam Fred Durst menguasai venue Woodstock 99.
Di tahun yang sama, sebuah kompilasi kemanusiaan dirilis untuk mengingatkan kontribusi musik pada bidang tersebut. No Boundaries, A Benefit for Kosovar Refugees menjadi album yang mengumpulkan kepedulian musisi untuk turut berderma dalam membantu korban perang Serbia-Kosovo. Minus Bob Dylan, tetapi Pearl Jam, Neil Young, Indigo Girls dan juga Rage Against the Machine menjadi ikon baru untuk band-band yang menyisakan kepedulian terhadap masalah yang berada di ujung berlawanan dari industri hiburan. Album ini kembali menghidupkan riak-riak protes sebelum masuk ke era millenium baru di mana sejumlah peristiwa internasional menyulut kontribusi dari industri musik untuk lebih peka.
Awal semester kedua tahun 2001, dunia diguncang oleh peristiwa kamikaze pesawat komersial ke bekas gedung tertinggi dunia, World Trade Center. Tragedi yang dikenal dengan nama 9/11 itu kemudian melahirkan dampak meluas bagi dunia. Amerika Serikat, negara adidaya yang relatif tidak pernah merasa terancam, dengan adanya peristiwa tersebut kemudian mulai melancarkan agitasinya untuk menunjukkan kekuatannya. Afghanistan dan Irak menjadi sasaran dalam lingkup yang lebih kecil. Dalam skala yang lebih besar, banyak hal yang terjadi di balik peristiwa tersebut, yang diantaranya permainan boneka-boneka kapitalis untuk membentuk dunia baru berlandaskan asas mereka. Hal itulah yang menginspirasi Michael Moore untuk melihat lebih dalam, dan mengungkapkan kecurigaan keterlibatan presiden Amerika Serikat, George Walker Bush dalam tragedi kemanusiaan tersebut. Melalui film dokumenter nan heboh-nya, bertitel Fahrenheit 9/11, Moore memberikan pandangan lebih luas mengenai latar belakang dan kemungkinan penyebab peristiwa 9/11 tersebut, dan juga motivasi-motivasi dibalik agresi militer AS ke Afghan dan Irak.
Moore merasa membutuhkan dukungan dari kalangan yang bisa membawakan pesan. Seperti halnya kesuksesan festival Woodstock dan kompilasi No Boundaries, Michael Moore mengumpulkan lineup dan ikon vokal dari industri musik yang peka terhadap masalah-masalah politik dan isu internasional serta kemanusiaan. Bob Dylan kembali hadir dan membawa Bruce Springsteen serta Pearl Jam untuk mengisi lineup kompilasi. Chimes of Freedom dan Master of War dibawakan oleh Springsteen dan Pearl Jam dalam performa live mengisi kompilasi. Kemudian mantan anggota Rage Against the Machine juga turut menyumbangkan dua karya dalam bentuk yang berbeda. Zack de la Rocha membuat komposisi rap-rock yang kental dalam We Want It All, sementara Tom Morello dengan side projectnya bertajuk Nightwtchmen menyanyikan ballad ala Dylan dalam No One Left.
Generasi baru diwakili oleh Black Eyed Peas dan System of A Down untuk membawa suara yang familiar dengan anak muda tahun 2000-an. Steve Earle, The Clash dan John Fogerty masih membawa nuansa generasi bunga tahun 70-an untuk bersikap kritis. Mendengarkan kompilasi ini, serasa membawa alam baru untuk berdemonstrasi positif terhadap pemerintahan. Kontribusi maksimal dari lagu-lagu yang dipilih, mulai dari empati atas korban perang, kebencian terhadap pertikaian politik dan sebaginya adalah suara-suara yang diwakili oleh musisi dalam kompilasi ini. Secara umum, membeli album ini adalah membeli suara dari barisan demonstran yang secara tegas menyuarakan pendapatnya dalam bentuk karya yang indah. Lineup yang terpilih juga merupakan estafet yang bagus untuk menunjukkan adanya ikon musisi yang peduli terhadap masalah kebangsaan dan kemanusiaan. Mulai dari era Bob Dylan yang merintis event Woodstock, sampai ke selera Black Eyed Peas yang mendominasi dekade 2000-an.
Lebih lanjut, beberapa alumni kompilasi ini kembali membuat festival kepedulian dalam tur Vote for Change. Pearl Jam, REM, Death Cab for Cutie dan sebagainya mewakili generasinya untuk bersikap oposan terhadap pemerintahan Bush. System of a Down dan Nightwatchmen membentuk Axis of Justice sebagai poros protes terhadap pemerintahan. Sementara Bruce Springsteen dan Bob Dylan adalah alumni yang menjadi begawan musisi-musisi untuk bersikap kritis!
Song lineup:
1. I Am A Patriot (And The River Opens For The Righteous) - Little Steven & The Disciples Of Soul
2. Chimes Of Freedom (Live) - Bruce Springsteen
3. With God On Our Side - Bob Dylan
4. We Want It All - Zack De La Rocha
5. Boom! - System Of A Down
6. No One Left - The Nightwatchman
7. Masters Of War - Pearl Jam
8. Travelin' Soldier - Dixie Chicks
9. Fortunate Son (Live) - John Fogerty
10. Know Your Rights - The Clash
11. The Revolution Starts Now - Steve Earle
12. Where Is The Love? (Radio Edit) - Black Eyed Peas Feat. Justin Timberlake
13. Good Night, New York (Live) - Nanci Griffith
14. Hallelujah - Jeff Buckley